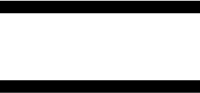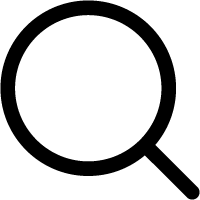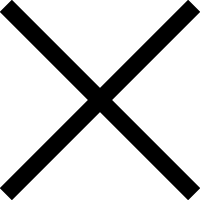Sekolah Rakyat Jadi Infrastruktur Kebudayaan Tumbuhkan Bangsa Yang Kuat
Oleh: Moeini Syakir
Di dalam khazanah filsafat kebudayaan, pendidikan selalu dipahami bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan kerja membentuk habitus, kebiasaan, cara memandang diri, dan horizon cita-cita. Karena itu, ketika negara menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai format terpadu (asrama, gizi, pembinaan karakter, hingga transformasi digital), yang sesungguhnya dibangun adalah “infrastruktur kebudayaan”: ekosistem yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan kapasitas untuk berdaya. Jejaknya mulai tampak di banyak titik, di Medan, Bantul, Sleman, hingga Tana Toraja dengan detail operasional yang rapi sekaligus narasi perubahan yang nyata dalam tubuh dan laku sehari-hari para siswa.
Di Medan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menerangkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 menampung 93 siswa dalam dua rumpun kelas (SD dan SMA). Ia menyebut seluruh siswa tinggal di asrama dengan 36 kamar, ruang guru, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung lain yang dirancang nyaman. Ia juga menjelaskan sekolah ini merupakan rintisan untuk menyalakan kembali semangat belajar, dengan rencana pembangunan gedung permanen di Medan Tuntungan mulai November 2025 hingga target selesai Juli 2026. Masih menurut penjelasannya, total lima sekolah rakyat dibangun di Sumatera Utara dengan alokasi anggaran Rp300 miliar; fokus infrastruktur bahkan merentang ke Nias berupa pembangunan jembatan gantung agar akses siswa ke sekolah terjamin. Pendidikan adalah soal struktur peluang, maka desain asrama, menjadi tempat aman, cukup gizi, fasilitas olahraga, adalah prasyarat dasar memberi ruang anak-anak belajar tanpa distraksi kemiskinan struktural.
Di Yogyakarta, SRMA 19 Bantul, rombongan media—dipandu jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital—mencatat kapasitas sekitar 200 siswa (116 perempuan dan 84 laki-laki) dari keluarga desil 1–2. Wakil kepala sekolah memaparkan bahwa seragam lengkap, tiga kali makan plus dua camilan, dan laptop yang mulai dibagikan merupakan standar dukungan. Seorang siswa, Dwi Hidayat, menuturkan rasa syukur karena dapat sekolah tanpa membebani orang tua buruh dan pemulung; ia menyebut pesan keluarga yang sederhana, sekolah sampai tamat, kalau bisa kuliah, sebagai motor cita-citanya menjadi guru. Testimoni seperti ini penting. Ia menandakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar layanan material, tetapi mesin pembentuk aspirasi, bahwa anak berani menyebut mimpinya di ruang publik.
Di SRMA 20 Sleman, Kepala Sekolah Reti Sudarsih menggambarkan lonjakan perubahan yang lebih kasatmata. Ia menerangkan bahwa dalam empat bulan, berat badan siswa rata-rata naik 5–11 kilogram, kebersihan diri membaik, hingga praktik pengawasan kecil namun konsisten (misalnya inspeksi kuku sebelum upacara) menghasilkan kebiasaan baru yang sehat. Asrama dua–tiga orang per kamar, ber-AC dan kamar mandi dalam; ruang kelas ber-AC, proyektor, smart board; jaringan internet 100 Mbps dari Kementerian Komunikasi dan Digital, serta bantuan laptop per siswa—semua itu menegaskan prinsip kesetaraan pengalaman belajar. Seorang siswi, Renata Merah, menyebut fasilitas sekolah “lebih dari cukup” dibandingkan rumahnya dan mengatakan dukungan ini membuatnya percaya diri mengejar cita-cita menjadi anggota TNI. Pada titik ini, kita melihat bagaimana kemewahan yang sesungguhnya dalam pendidikan adalah rasa layak; peralatan digital hanyalah instrumen untuk menegaskan bahwa anak-anak prasejahtera berhak mengalami kualitas yang sama dengan sekolah unggulan.
Dimensi kebudayaan Sekolah Rakyat juga tampak melalui kolaborasi literasi. Di SRT 62 Tana Toraja, Tim Ekspedisi Patriot ITB bersama BRIN dan Gramedia meluncurkan program “Kita Membaca”: 400 buku dan empat rak baca asrama diserahkan; pendekatan “Sebaya Membaca” dirancang agar siswa yang lebih lancar menjadi pendamping bagi teman-temannya. Koordinator program—dengan latar riset tentang kawasan transmigrasi—menerangkan bahwa inisiatif ini sengaja melampaui laporan akademik: buku dan praktik membaca di asrama dimaksudkan sebagai kegiatan positif yang memupuk empati, disiplin, dan rasa ingin tahu. Kepala sekolah menyampaikan apresiasi dan harapan agar dukungan ini menumbuhkan kecintaan pada dunia buku. Dalam kacamata filsafat pendidikan, intervensi semacam ini memulihkan inti humaniora: kemampuan menunda impuls, menimbang makna, dan membangun cakrawala bersama melalui teks.
Ekosistem digital pun dirangkai sebagai pengalaman setara, transformasi digital di Sekolah Rakyat dimaksudkan untuk menghadirkan kualitas kurikulum dan proses belajar yang tak kalah dari sekolah swasta unggulan. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan, infrastruktur digital merupakan landasan utama bagi pemerataan pendidikan. Fasilitasi internet cepat, smart board di setiap kelas, sampai penyiapan Learning Management System (LMS) yang akan diimplementasikan pada semester depan menunjukkan bahwa “modernitas” tidak boleh eksklusif. Di sini, digitalisasi bukan tujuan, melainkan medium untuk memperluas akses, memperkaya metode, dan menyiapkan literasi baru—sekaligus mengoreksi ketimpangan lama yang membuat anak miskin menghadapi masa depan dengan perangkat usang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan kebangsaan adalah keberanian anak-anak menyebut mimpinya tanpa merasa mengada-ada. Kita sedang menyaksikan kebudayaan bekerja. Sekolah Rakyat, dalam pengertian itu, bukan proyek karitatif, melainkan politik martabat, cara negara berkata bahwa setiap anak Indonesia berhak atas ruang yang aman, tubuh yang sehat, akal yang terlatih, dan masa depan yang dapat dibayangkan. Itu sebabnya, konsistensi pembangunan fisik, disiplin pengasuhan, dan kolaborasi literasi mesti dijaga. Sebab dari kebiasaan yang baik, lahirlah warga yang baik, dan dari warga yang baik, tumbuhlah republik yang kuat.
*) Pemerhati Kebijakan Publik